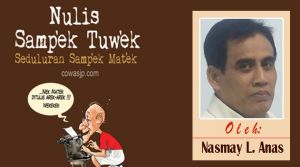COWASJP.COM – ockquote>
O l eh: Dhimam Abror Djuraid
------------------------------------------
‘’Bawa senjata namanya makar, bawa seperangkat alat shalat namanya mahar’’.
ITU Itu adalah salah satu saja dari ribuan atau puluhan ribu meme yang beredar di dunia siber belakangan ini. Setelah demo besar 411 sekarang ada lagi demo 212. Dunia seolah terbelah menjadi dua, pro dan kontra, setuju tidak setuju. Satunya mendukung, lainnya menyerang. Media terbelah menjadi dua, ada yang pro dan ada yang kontra, setiap hari 24 jam tidak pernah berhenti informasi mengalir tak pernah jeda. Kita sedang berada pada masa ketika informasi yang tidak kita butuhkan mengalir tiada henti setiap menit setiap detik.
Meme makar dan mahar itu bisa menjelaskan keterpecahan opini di masyarakat sekarang ini. Secara sederhana pengelompokan bisa dibagi menjadi dua: kelompok yang setuju 212 disebut sebagai—untuk menyederhanakan kategorisasi—‘’Kelompok Makar’’, sedangkan kelompok yang tidak setuju 212 sebut saja—sekali lagi, untuk menyederhanakan kategorisasi—sebagai ‘’Kelompok Mahar’’.
Tentu tidak sesederhana itu. Yang disebut segagai Kelompok Makar pasti tidak senang dengan sebutan itu, karena jelas konotasinya adalah mengangkat senjata untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
Sedangkan Kelompok Mahar juga pasti tidak senang dengan sebutan itu, karena konotasinya—sebagaimana dalam sebuah perkawinan--mereka menerima ‘’sesuatu’’ untuk sebuah koalisi ‘’perkawinan’’ politik.
Kedua kelompok itu sekarang sedang bertarung sengit. Menjadi semakin sengit karena ditumpangi oleh pertarungan antar-elit politik. Kasus Ahok mungkin bisa diibaratkan sebagai puntung rokok. Ketika Anda membuangnya pada tempat yang betul tidak akan menjadi masalah. Tetapi, sekarang yang terjadi adalah Anda membuangnya di POM bensin. Tak ayal, meledaklah depo itu dan kebakaran besar terjadi, dan bisa merantak lebih besar dan tak terkendalikan.
Timbunan minyak yang membara itu sudah menjadi sekam bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, dan bahkan berabad-abad. Ada sense of losing, perasaan kalah, perasaaan terpinggirkan, termarjinalisasikan selama bertahun-tahun atau berabad-abad itu. Sekarang sekam itu menjadi api besar karena tersulut puntung rokok yang dilempar secara sembarangan.
Mayoritas Islam di Indonesia telah lama kehilangan rasa sebagai pemilik rumah yang berdaulat. Sejak zaman kemerdekaan, kelompok Islam terpinggirkan oleh kebijakan devide et impera yang diterapkan oleh penjajah Belanda. Segregasi sosial sengaja dilakukan penjajah untuk memperlemah masyarakat.
Kaum pribumi yang diasosiasikan dengan Islam disebut sebagai kelompok kelas dua. Sebuah degradasi yang menyakitkan karena dialami di rumah sendiri. Sedangkan kelompok kulit putih dan kuning, termasuk Cina, dikategorikan sebagai masyarakat kelas satu. Segregasi itu diperkuat dengan segregasi agama. Kelompok kelas satu adalah kelompok Nasrani sedangkan kelompok kelas dua adalah kelompok muslim.
Sejak itu bibit perpecahan tumbuh berakar dan menjadi sekam yang setiap saat siap menjadi kebakaran besar. Kelompok kelas satu beroleh privilij ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kelompok kelas dua terdegradasi dan termarjinalisasi nyaris menjadi pariah. Dengan segregasi itu penjajah melemahkan perlawanan dan melanggengkan kekuasaan.
Ketika kemudian kekuasaan penjajahan runtuh dan Soekarno menjadi presiden, ketimpangan ini yang dicoba diatasi. Ketertinggalan ekonomi kelompok pribumi coba diatasi dengan Program Benteng dengan memberi kemudahan akses ekonomi kepada penguasaha pribumi supaya mampu bersaing dengan pengusaha Cina. Proyek ini tidak berhasil sampai Soekarno jatuh dan digantikan Soeharto.
Soeharto tidak ingin mengulangi kesalahan Soekarno yang gagal mengarbit pengusaha pribumi untuk menjadi raksasa yang menjadi motor perkembangan ekonomi. Soeharto melakukan hal yang sebaliknya. Ia memberikan privilij ekonomi kepada pengusaha Cina, mengarbitnya menjadi konglomerat besar dengan harapan kekayaan konglomerat itu akan meluber ke rakyat bawah menghasilkan ‘’trickle down effect’’ sebagaimana teori Rostov.
Sambil memanjakan kelompok minoritas Cina dengan berbagai kemudahan ekonomi Soeharto, pada saat bersamaan, mengekang hak-hak budaya dan politik Cina. Bahkan identitas Cina paling azasi seperti nama pun dihapus oleh Soeharto. Maka lahirlah Sudono Salim, Mohammad Hasan, William Soeryajaya, Prajogo Pangestu, dan sederet lainnya. Mereka hanya minoritas kecil, tidak lebih dari 7 persen, tetapi menguasai ekonomi nasional sampai 90 persen. Sungguh sebuah ketimpangan yang sangat menganga dan berbahaya.
Tidak ada negara di dunia demokratis yang mengalami gap sosial selebar itu. Hanya sebuah rekayasa sosial yang teliti dan dikawal dengan kekuatan otoritarian yang konsisten yang bisa mengatasi problem itu. Itulah yang dilakukan Mahathir Mohammad di Malaysia. Kelompok Melayu Bumiputra disemai, dipupuk, dan ditumbuhkan, dan dibesarkan supaya bisa bersaing dengan kelompok Cina. Mahathir dituduh rasis dan bahkan fasis. Tetapi, Mahathir bergeming, dan rekayasa sosialnya sekarang membuahkan hasil.
Di Singapura Lee Kuan Yew membuat rekayasa sosial besar untuk mengangkat bangsa Cina yang mayoritas menjadi motor kemajuan ekonomi. Pada akhir 1960-an ketika memisahkan diri dari Malaysia, Singapura adalah dunia ketiga yang terbelakang, jorok, dan miskin. Lee dengan keteguhan, ketekunan, dan disertai dengan kekuatan tangan besi, melakukan rekadaya sosial sehingga dalam tempo tiga dasawarsa Singapura berubah dari dunia ketiga menjadi dunia pertama. Dalam proses itu Lee dituduh memarginalisasi kelompok minoritas Melayu, tapi Lee tidak peduli.
Rekayasa sosial raksasa lainnya dilakukan Deng Xiao Ping di Cina. Sebuah negara dengan lebih dari satu miliar mulut untuk diberi makan setiaphari. Populasinya homogen tetapi dengan kualitas sumber daya yang rendah dan tidak disiplin. Deng mengubah pola pikir Cina yang terbelenggu doktrin komunisme yang kaku selama puluhan tahun menjadi pola pikir yang pragmatis yang menjadi ciri khas konfusianisme Cina.
Deng tahu persis karakter pragmatis Cina, dan karenanya ia (sementara) melepaskan jaket ideologi komunisme dan mengumumkan bahwa kaya itu mulia, rakus itu bagus. Tak peduli kucing hitam atau putih asal bisa menangkap tikus. Sebuah rekayasa sosial yang revolusioner dikawal oleh kekuatan senjata partai komunis yang disiplin menghasilkan sebuah revolusi ekonomi yang lebih dahsyat dibanding revolusi komunis 1949.
Deng dan Lee pergi mewariskan legasi yang kokoh. Mahathir membangun pondasi yang kuat.
Soeharto jatuh, dan kemudian pergi meninggalkan warisan yang rapuh dan porak poranda. Proyek rekayasa sosialnya ambruk. Segala pengekangan terhadap kelompok Cina turut roboh bersama tumbangnya rezim Orde Baru yang dibangun Soeharto. Hak-hak politik dan budaya Cina yang semula dirampas dikembalikan bersama uforia reformasi. Kekuatan ekonomi yang gigantik yang dimiliki orang Cina Indonesia dengan mudah bisa membeli kekuatan politik melahirkan perpaduan yang dahsyat.
Pada titik inilah kekecewaan pribumi muslim mencapai titik didih. Pada masa Belanda termarginalisasi, pada masa Orde Baru dicurigai dan dipinggirkan. Sekarang pada era reformasi terpinggirkan karena kalah dalam persaingan modal. Maka pada posisi ini Ahok menjadi penyulut yang paling efektif untuk mengobarkan api besar yang dalam sekejap bisa meruntuhkan rumah kebangsaan kita.
Harus ada rekayasa sosial untuk menyelesaikan persoalan besar ini. Tak bisa hanya diserahkan kepada pasar. Tak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme ‘’tangan yang tidak kelihatan’’, the invisible hand kapitalisme. Lupakan Makar. Lupakan Mahar. Sekali lagi, harus ada rekayasa sosial ala Mahathir, ala Lee, atau ala Deng. Indonesia butuh orang kuat sekarang ini. Sekarang juga! (*)